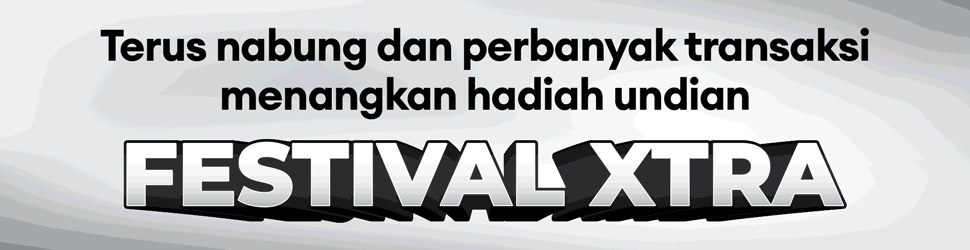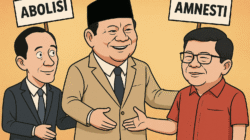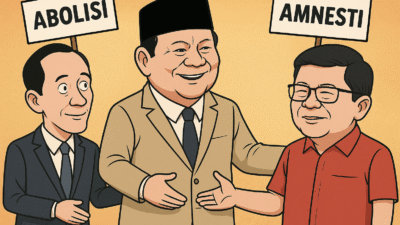Oleh : Fadli Baharudin*
Sebulan belakangan sosok Rismon Sianipar tengah melambung mengangkasa. Amat sering mengisi layar beranda mayantara. Sabankali video pernyataannya diunggah ke platform virtual, kolom kicau langsung dibanjiri ribuan komentar netizen.
Serupa zat adiktif, tiap bunyi kalimat yang menyertai pernyataannya menarik antusiasme dan memancing adrenalin. Sulit rasanya untuk tidak menyimak. Logat khas Medan kian memberi kesan ngeri-ngeri sedap terhadap apa yang disibaknya. Mendengarnya berbicara, pikiran serasa dipukul dari kepasrahan, menyentak kesadaran bahwa ada belenggu yang tengah mengekang nalar, sadar atau tidak.
DR. Rismon Hasiholan Sianipar memperkenalkan dirinya sebagai brainware yang ahli di bidang digital forensik. Pengakuannya itu sudah terkonfirmasi, lewat dokumen tangible, juga lewat bukti digital forensik, secara afirmatif, tanpa bertele-tele.
Rismon adalah satu dari sedikit yang tetap mendudukkan sains atau ilmu pengetahuan sebagai episentrum etik-moral, yang memang mestinya dijadikan perangkat untuk menjaga martabat atau derajat kemanusiaan, dan bukan malah menjadikannya alat menistai diri. Manusia tidak seharusnya menyerupakan diri seperti hewan, dan Rismon tegas pada prinsip itu.
Namun, di Indonesia, berlayar dengan prinsip itu memang membutuhkan tekad dan keberanian. Ombak perlawanan besar menghantam. Sebab, hakikatnya manusia tidak sedang berseteru dengan sesama manusia, melainkan dengan demon si pembisik yang memperalat manusia lewat tipu muslihat, lewat ketamakan. Dan tentu saja, demon si pembisik amat benci untuk urusan etik-moral.
Apa yang ditunjukkan Rismon setidaknya mengundang simpati luas dari rakyat, kalau bukan decak kagum. Sebab, banyak benak yang mengetahui bertumpuk skandal hadir di pusaran negara dan merasa tak aman atas kondisi itu. Namun, berbilang yang punya nyali meneriakkan, sebab taruhannya tidak main-main. Munir, Wiji Thukul, Marsinah, Novel Baswedan, Bambang Tri, Gus Nur adalah di antara deretan contoh.
Rismon tampil dengan nyali. Dengannya ia menjadi beken, seperti oase di gurun pasir.
Nyalinya memang luar biasa. Nyali yang memekik karena jemu pada ketimpangan nilai dan cengkeraman otoritas yang manipulatif. Rismon punya keyakinan, bahwa sejarah menyimpan catatan, mereka yang bernyali menukar hidup untuk kebenaran akan dikenang sebagai ksatria.
Di lautan kemunafikan dan gelombang kepengecutan, nyali memang menjadi entitas mewah. Dan lelaki Batak itu memutuskan bertaruh; memilih konsisten pada kebenaran dengan resiko ancaman keamanan atau tunduk dalam bayang-bayang kebodohan dursila dengan imbalan kemasyhuran semu.
Rismon menjadi anomali. Dikatakan anomali karena dia “aneh” di lautan “ketidakanehan”. Mirip Rocky Gerung, seperti Cak Nun. Memilih bersuara ketimbang kekuasaan tetapi bungkam.
ANEH yang dimaksud adalah sikap teguhnya menyuarakan kebenaran autentik. Nalar atau logika an sich adalah senjatanya. Menjadi aneh karena jumlahnya secuil.
Dan definisi KETIDAKANEHAN disitu, seperti biasa, adalah menempatkan preferensi mainstream linear sebagai kebenaran. Perbedaan, atau bahkan perlawanan terhadapnya, dituduh sebagai ketidaknormalan, mengganggu keseimbangan sehingga tak mengapa untuk dibinasakan. Uang, juga kekuasaan, adalah preferensi mainstream. Kebenaran dimonopoli oleh pemilik uang dan kekuasaan. Dia menjadi “tidak aneh” sebab penganutnya melimpah.
Bila diteliti, apa yang dilakukan Rismon bukanlah hal luar biasa seandainya itu berlangsung di negara “normal”. Menjadi perhatian luas audiens lantaran, di Indonesia, sepak terjangnya tampak anomali. Ya itu tadi, karena berseberangan dengan predikat preferensi mainstream.
Pernyataan blak-blakan dirinya dengan mengatakan telah terjadi manipulasi bukti digital kasus kopi sianida Mirna dan menyebut Tito Karnavian sebagai dalangnya adalah bentuk keberanian melawan dominasi mainstream.
Begitu pula tuduhan ijazah palsu Jokowi yang ia lontarkan. Mungkin, Rismon tengah mencari sensasi. Tapi, setidaknya apa yang ia sampaikan memiliki landasan cukup, bersesuaian dengan pembuktian keahlian yang ia miliki yakni ilmu di bidang digital forensik. Hati kecil bisa merasakan frekuensi, bahwa hal itu tidak asal-asalan.
Dalam konteks perwujudan sistem demokrasi, tindakan Rismon amat lumrah. Justru dia membuka ruang dialektika, tesis-antitesis-sintesis, sebagaimana itu menjadi landasan filsafat Hegel, sejak dulu. Rismon menghidupkan daya kritis.
Tinggal, jika dianggap tidak sesuai, Tito maupun Jokowi melancarkan antitesis. Dari dialektika keduanya, serahkan lembaga peradilan membuat sintesis (tentu peradilan bersih serta objektif). Vonis kebenaran bagi nama baik dan demi keterbukaan, sementara putusan kesalahan bagi yang menerima konsekuensi. Toh, itu yang diinginkan Rismon. Laporkan dirinya, agar adu pembuktian bisa dilakukan secara formal dan terlembaga.
Hanya saja, Tito maupun Jokowi cenderung bungkam. Memilih kegaduhan berlarut-larut. Dan rasanya kita semua sepakat membiarkan situasi seperti itu bukanlah pilihan bijaksana apalagi terbaik, kecuali memang Tito atau Jokowi tak memiliki dalil kuat untuk menjungkirbalikkan tuduhan.
Dan agaknya, fenomena pengecualian itu yang kuat terasa. Pasalnya, tak sulit rasanya membantah bila tuduhan Rismon tak sesuai. Jokowi, misalnya, tinggal menunjukkan ijazah aslinya tanpa harus buang-buang energi melibatkan rektorat UGM dan sederet pengacara. Untuk apa menggunakan cara ribet bila ada yang lebih efektif-efisien. Begitu pula dengan Tito.
Namun, justru yang dipertontonkan, logika sederhana itu ingin dipatahkan dengan berbagai akrobat yang panjang dan berbelit. Dari satu argumentasi berpindah ke satu narasi. Padahal perkaranya simpel. Maka bolehlah publik menangkap kejanggalan, bahwa naga-naganya tuduhan itu benar adanya. Lalu, berbaris di sisi Rismon mendukung pengungkapan tuduhan.
Anomali Rismon bukanlah sekadar persoalan mencari benar-salah atau baik-buruk, tapi landasan utamanya bertujuan mengingatkan kita untuk tidak melenceng jauh dari fitrah, gampang termakan hasut dan tipu daya demon si pembisik. Ada harkat dan martabat berharga mahal dipertaruhkan disitu, yang mesti dirawat dengan penuh kebanggaan. Sebab, cuma itu tiket dapat kursi di akhirat.
Pertanyaannya, apakah Rismon tetap konsisten dengan perjuangannya atau justru sebaliknya ?
Entahlah.
*Penulis adalah warga di Kelurahan Tanamodindi – Palu