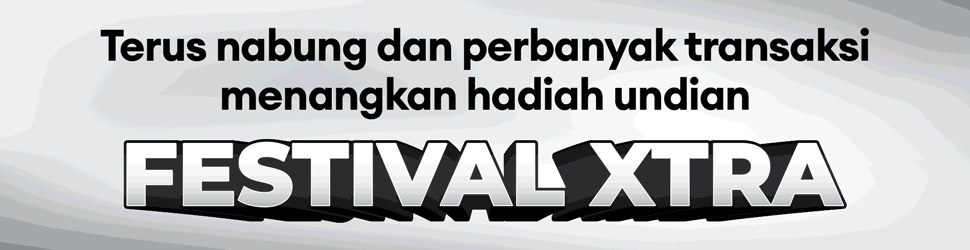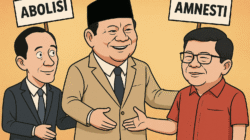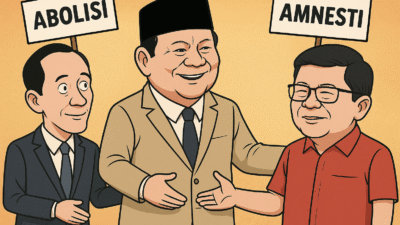Oleh : Dr. Saifudin Zuhri
Untuk kali kesekian intoleransi terjadi lagi di negeri ini. Siang itu, Jumat (27/06/2025), rumah singgah atau vila di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, dirusak sejumlah warga ketika sekelompok anak dan remaja yang beragama Kristen tengah menjalani retret.
Kasus tersebut menambah daftar panjang peristiwa intoleransi di Indonesia. Menurut Laporan Human Rights Watch dan Setara Institute menunjukkan bahwa angka kekerasan atas nama agama di Indonesia mencapai 175 kasus. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan apa akar permasalahan yang sesungguhnya? Bagaimana cara menangani permasalahan intoleransi selama ini? Mengapa selalu berulang dan bahkan berpola?
Jika dipetakan akar permasalahan intoleransi di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Pertama: bersumber dari proses terbentuknya negara bangsa (nation-state) Indonesia itu sendiri. Berbeda dengan proses terbentuknya negara bangsa sekuler sebagaimana yang terjadi di Eropa, negara merupakan sistem antitesis terhadap sistem sebelumnya, yakni feodalisme dan dogmatisme agama. Dengan demikian kehadiran negara sepenuhnya mengganti segala hal yang dibawa dari sistem lama yang dianggap irasional, diskriminatif, dan menindas dengan sistem hukum positif yang lebih terukur dan melindungi hak-hak seluruh warga negara secara adil, setara, dan obyektif.
Terbentuknya bangsa Indonesia memiliki proses sejarah yang berbeda. Negara Indonesia merupakan hasil konsensus yang mengkompromikan 3 unsur sekaligus dalam satu bejana besar (melting pot) yang bernama negara. Ketiga unsur itu adalah adat istiadat, agama, dan negara.
Berbeda dengan konsep negara dari Barat yang berpola tegas dan lugas membetuk thesa dan anti-thesa, Indonesia lebih memilih pola holistik yang bersifat kompromistis, karena itu nilai-nilai yang diwariskan sistem lama (adat istiadat dan agama) tidak sepenuhnya dibuang dari sistem ketatanegaraan. Konsekwensi dari pilihan ini adalah walaupun Indonesia sudah menjadi negara hukum dan bersistem demokrasi, bias pengaruh sistem lama masuk dalam kehidupan bernegara.
Terutama menyikapi kasus menyangkut kehidupan beragama, pemerintah dibuat serba dilematis dan serba canggung. Pada satu sisi negara harus tegas dan konsisten dalam penegakan hukum positif namun pada satu sisi impresi normatif yang diusung oleh dogma agama memerintahkan pemeluknya untuk menaatinya.
Problem muncul ketika atas nama ketaatan terhadap norma agama dan fanatisme nilainya berbenturan dengan komunitas agama yang berbeda. Persoalan menjadi kian pelik ketika bersinggungan dengan komposisi umat mayoritas. Inilah akar masalah pertama mengapa intoleransi berulang terjadi.
Kedua, dogmatisme agama smetik Islam dan Kristen. Selain kedua agama tersebut memang ada agama lain yang ada di Indonesia, seperti Hindu, Budha, Khonghucu, dan aliran kepercayaan, akan tetapi khusus antara Islam dan Kristen memiliki akar sejarah konflik yang sudah muncul sejak dari awal mula kelahirannya. Bahkan kedua agama tersebut lahir dari konflik itu sendiri yang berasal dari wilayah yang non jauh di sana. Persaingan, klaim kebenaran, dan konflik bukan hanya menjadi causa historis kedua agama smetik itu, namun juga terkonstruksi dalam sistem ajaran dan cara membangun identitas penganutnya.
Untuk menyangkal karakter kedua agama tersebut sering menyajikan narasi yang seakan kebalikannya, seperti umat Islam mempromosikan ajaran “rahmatan lil’alamin” dan umat Kristen membranding diri dengan ajaran “kasih”.
Namun, pada kenyataannya kedua agama tersebut merupakan agama misi yang saling bersaing. Nilai-nilai yang dibranding adalah dalam rangka promosi dan berebut pengaruh. Khusus umat Islam agresifitas dan sensitifitas terhadap umat Kristiani adalah bentuk kekhawatiran terhadap dominasinya sebagai mayoritas yang selama ini dinikmati.
Ketiga, kapabelitas negara. Dalam konstitusi Republik Indonesia dinyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara berdiri di atas semua golongan sebagai negara hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu. Aparatur negara harus netral tanpa memihak kepada semua warga negara. Hukum mestinya menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Negara harus adil sebagai pengadil jika terjadi konflik antar agama berdasar bukti-bukti hukum positif, bukan atas presure mayoritas, loby, dan konspirasi.
Namun nampaknya seluruh harapan tersebut tak selalu diperankan dengan baik oleh aparat penegak hukum dan pemimpin bangsa ini. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan mengatur hubungan antara negara dan agama sudah menjadi bagian dari sejarah berdirinya bangsa ini sebagaimana diurai pada point pertama tersebut di atas. Sementara dinamika politik kekinian mengkapitalisasi agama bukan sebagai sumber moral namun sebagai instrumen untuk membangun kekuasaan.
Itulah ketiga faktor yang menjadi akar masalah mengapa konflik antar agama (terutama Islam-Kristen) sering terjadi dan berulang tanpa solusi yang berarti. Bibit konflik antar umat beragama – terutama Islam vs Kristen – adalah problem teologis sekaligus mencerminkan kemampuan bangsa ini dalam bernegara. Sedihnya adalah, sementara bangsa-bangsa lain sudah berkembang cepat menyambut era kemajuan teknologi, bangsa Indonesia masih berkutat pada isu agama yang di dunia lain sudah ditinggalkan sejak abad pertengahan.
*) Penulis ada dosen dan peneliti tinggal di Yogyakarta