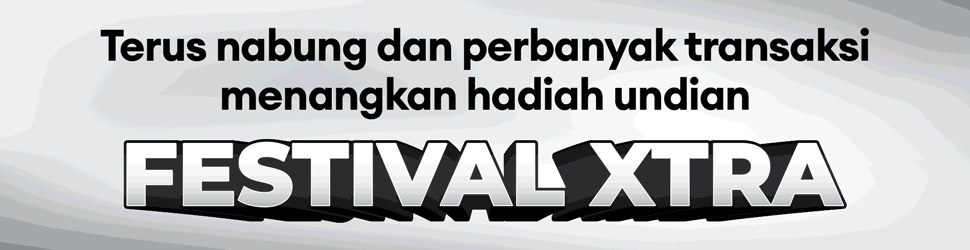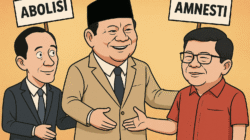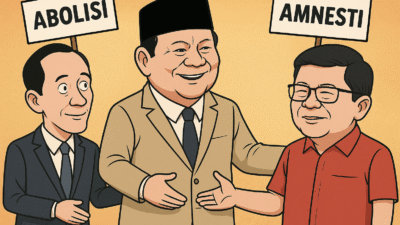Oleh Saifudin Zuhri *
Bangsa ini begitu kaya akan simbul. Khazanah simbul itu memenuhi di berbagai entitas sosialnya, sejak dari budaya, agama, dan negara. Bagi bangsa Indonesia simbul bukan hanya media ekspresi sebuah nilai dan identitas, namun lebih dari itu simbul menjadi media interaksi sosialnya sehari-hari. Tidak berlebihan jika dikatakan inilah bangsa yang paling fasih mengejawantahkan predikat manusia sebagai “homo syimbolicum”.
Istilah “homo symbolicum” muncul dalam kajian ilmu antropologi dan filsafat untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang menggunakan simbol. Tokoh dibalik teori tersebut adalah Ernst Cassirer, seorang filsuf Jerman (1874-1945) dimana pemikirannya dituangkan dalam karyanya yang berjudul “An Essay on Man” (1944).
Dalam konsep “homo symbolicum” manusia menggunakan simbol sebagai ciri khas yang membedakan dengan makhluk lain. Dengan simbul itu pula memungkinkan manusia untuk menciptakan budaya, bahasa, seni, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Oleh karena itu simbul memiliki arti penting dalam kehidupan manusia dan dari simbol itu pula pemahaman manusia tentang dunia terbentuk.
Teori tersebut relevan untuk menganalisis fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. One Piece adalah bendera dengan simbul ikonik gambar tengkorak mengenakan topi jerami yang ada dalam film anime karya Eiichiro Oda. Simbul tersebut mencerminkan keberanian dan identitas kru Topi Jerami dalam petualangan mereka di dunia One Piece.
Fenomena tersebut muncul sebagai bentuk reaksi satir generasi kekinian (terutama zelenial) dalam merespon perkembangan situasi dunia sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini.
Dalam algoritma media sosial memang terdengung kebisingan menyangkut isu tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populis, tidak adil, dan tidak berpihak pada rakyat. Pengibaran bendera One Piece di bawah sangsaka Merah Putih merupakan simbul ekspresi generasi zelenial yang protes pada keadaan yang tidak sesuai harapan. Bendera One Piece menginspirasi semangat memperjuangan nilai-nilai keberanian melawan kedzaliman.
Pengibaran bendera One Piece pada momentum sakral memperingati hari kemerdekaan tentu mengundang reaksi beragam dari berbagai elemen masyarakat.
Bagi generasi zelenial sendiri aksi ini merupakan ekspresi jenaka nan satir dan justru bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negaranya dengan memanfaatkan pop culture. Namun bagi kelompok formalis yang notabene berasal dari generasi yang lebih tua, aparatur pemerintah, dan militer menanggapi negatif dan tidak pantas yang karena itu harus dilarang.
Secara sosiologis mengapa bangsa ini begitu konsern dengan hal-hal yang bersifat simbolik? Apa makna simbol dalam sistem sosial masyarakat? Apa dampaknya terhadap peradaban bangsa ini?
Simbul dalam kehidupan masyarakat tidak berdiri sendiri. Simbul merupakan representasi sebuah nilai esensi tertentu yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk khusus sebagai identitas sekaligus media untuk mengkomunikasi nilai dalam interaksi sosial. Simbul terkait dengan teori kontruksi sosial. Dalam teori ini relevan untuk meminjam konsep yang dikemukakan oleh sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam karya sosiolog tersebut yang berjudul “The Social Construction of Reality” (1966), menjelaskan bagaimana realitas sosial dikonstruksi oleh individu dan masyarakat melalui tiga proses, yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.
Eksternalisasi proses di mana individu atau kelompok mengungkapkan pikiran, nilai, atau makna ke dalam dunia luar melalui tindakan atau ekspresi, seperti norma, institusi, atau artefak budaya.
Objektivasi merupakan tahap di mana produk-produk yang sudah eksternalisasi itu menjadi objek yang berdiri sendiri di luar individu sehingga tampak objektif bagi anggota masyarakat. Sedangkan internalisasi proses di mana individu menyerap realitas sosial yang telah dikonstruksi dan objektivasi tersebut, sehingga menjadi bagian dari kesadaran dan identitas mereka.
Hubungan antara eksternalisasi – obyektifikasi – internalisasi simbul terjadi dalam dialektika secara terus menerus dan dinamis dalam kehidupan individu dan masyarakat. Jika salah satu proses simbolisasi itu terhenti atau terputus maka salah satu tahapannya akan membeku, kehilangan makna, dan tercerabut dari kontruksi realitas sosial. Demikian halnya realitas simbul yang diproses dari ketiga tahap tersebut.
Fenomena bendera One Piece bisa dianalisis dengan teori tersebut. Generasi zelenial yang hidup di era teknologi digital menjadikan isu pengibaran bendera One Piece pada momentum HUT ke-80 RI bukan tanpa makna. Bendera Merah Putih maupun One Piece sebenarnya sama-sama simbul, hanya saja sangsaka Merah Putih secara historis dan konstitusional merupakan lambang negara, sedangkan bendera One Piece merupakan fenomena budaya pop yang tidak lama lagi juga akan berganti oleh budaya pop lainnya.
Hanya saja fenomena ini menjadi menarik dalam konteks fungsi simbul dalam ketiga proses tersebut (eksternalisasi – obyektifasi – dan internalisasi).
Gerakan pengibaran bendera One Piece adalah ekspresi satir kelompok masyarakat yang justru ingin terlibat dalam eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi esensi simbul sang pusaka Merah Putih di momentum suci hari kemerdekaan. Selama ini diajarkan bahwa simbul warna putih berarti suci dan merah berarti berani, namun kontruksi makna tersebut kontradiktif dengan realitas yang dijumpai masyarakat.
Di tengah kekeringan makna oleh simbul nasionalisme yang selalu dijejalkan, kelompok kritis ini mencoba melawan dengan menghadirkan simbul tandingan, bukan untuk merendahkan simbul negara namun justru inilah bentuk cinta sejati yang tidak rela kesucian dan keagungan simbul hanya sekedar simbul belaka tanpa makna, tanpa jiwa, dan tanpa realitas.
Generasi yang hidup di zaman ini memang tidak terlibat langsung dalam proses kelahiran simbul negara, namun bukankah masa depan negeri ini ada di tangan generasi muda yang berhak terlibat dalam proses produksi makna.
Bangsa ini sangat kaya simbul sekaligus pemuja simbul. Teramat banyak karya-karya simbolik di berbagai aspek kehidupannya. Jika simbul-simbul itu dibiarkan membeku tanpa ada upaya reaktualisasi makna bisa jadi simbul-simbul itu akan membeku dalam artefak sejarah tanpa makna.
Simbul yang dibiarkan berserak dan membisu tanpa makna akan membuat simbul itu mengering dan semakin kehilangan fungsinya. Lebih dari itu, khazanah simbolik ini bisa jadi akan saling berbenturan yang melibatkan institusi yang mengkonstruksi simbul, yaitu institusi budaya, agama, dan negara.
Simbul budaya yang mengering akan mereduksi simbul sebagai artefak seni tanpa esensi, adat tanpa jiwa, dan menjadi komoditas pariwisata semata. Simbul agama yang mengering akan menjadikan ritual tanpa makna dan dogma bagai berhala. Simbul negara yang mengering akan mendegradasi simbul hanya sekedar seremoni tanpa arti dan semboyan tanpa makna. Simbul budaya, agama, dan negara yang sudah terobyektifikasi akan sulit diinternalisasi oleh individu dan masyarakat ketika terjadi divergensi antara tujuan pembuatan simbul dengan realitas obyektifnya.
Budaya, agama, dan negara yang oleh Soekarno diramu menjadi satu kesatuan yang disebut “triprakara” sebagai kausa meterialis Pancasila, akan mengalami divergensi fungsi dalam merajut kesatuan bangsa. Divergensi ketiga subyek simbul bukan hanya berakibat pada pemudaran daya rekat antar ketiga unsur yang dulu mampu disatukan, namun berpotensi antar entitas itu saling mengklaim kebenaran dan saling menistakan.
Jika generasi sekarang hidup di era yang berjarak jauh dengan sumber dan proses pembentukan simbul, harus disisakan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam penafsiran ulang menurut cara mereka sendiri. Itulah cara membuat simbul tetap hidup, bermakna dan berfungsi.
Kritik satir generasi muda mengangkat simbul bendera One Piece bisa jadi indikator bahwa simbul negara semakin memudar, atau paling tidak, kehilangan makna ketika kemegahan simbul yang dibanggakan berjumpa dengan realitas yang bertolak belakang. Merah tidak lagi berani, dan putih tidak lagi suci.
*(adalah dosen tinggal di Yogyakarta