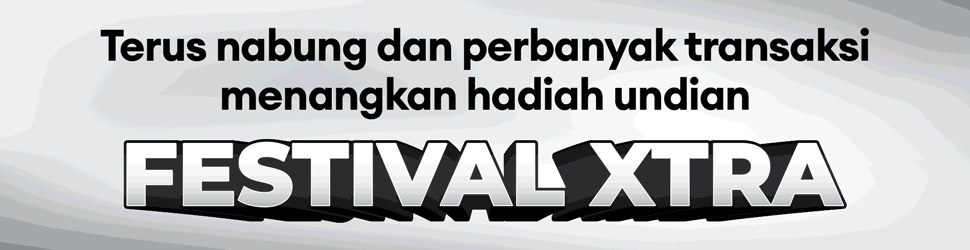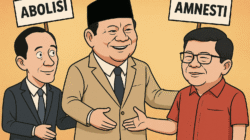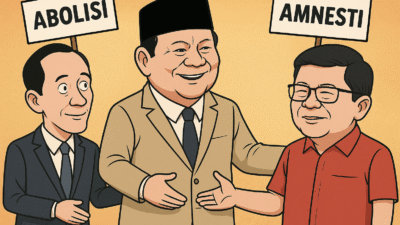Oleh Dr. Saifudin Zuhri*)
Serasa buntu harus darimana mengurai benang kusut negeri ini. Gejolak massa berujung anarkhisme di berbagai daerah di Indonesia baru-baru ini menambah daftar panjang sejarah kerusuhan massa yang pernah terjadi di negeri ini.
Sampai saat ini masih belum pasti sampai kapan tragedi ini berakhir? Siapa atau kekuatan apa yang sesungguhnya berada di balik semua peristiwa memilukan ini? Belum terjawab pertanyaan itu aksi anarkhisme dan penjarahan mulai menjalar di berbagai daerah dan menyasar obyek-obyek yang menjadi simbol ketidakadilan, penindasan, lembaga-lembaga publik, dan bahkan orang per orang.
Sebagaimana peristiwa kerusuhan massa yang terjadi sebelum-sebelumnya, konflik di Indonesia selalu memiliki dua dimensi, yakni eksternal dan internal.
Eksternal adalah kekuatan global yang memiliki kepentingan di Indonesia kemudian mengintervensi baik secara langsung atau tidak langsung. Kekuatan itu bisa berupa korporasi trans-nasional maupun kepentingan geopolitik negara tertentu.
Sedangkan dimensi internal adalah pertarungan antar kelompok kepentingan yang saling berebut pengaruh di Indonesia, baik dalam ranah ideologi, politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya.
Layaknya perubahan sosial (sosial change) yang terjadi di berbagai peradaban dunia, selalu didahului dengan peristiwa kerusuhan sosial bahkan perang. Penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789 adalah contoh simbol dimulainya Revolusi Perancis.
Demikian halnya huru-hara kerusuhan Mei 1998 di Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi yang merubah lanskap politik di Indonesia menjadi lebih bebas daripada era sebelumnya yang otoriter.
Perubahan sosial bahkan revolusi selalu dibarengi dengan perjuangan dan pengorbanan. Persoalannya adalah apakah semua itu terbayar dengan hasil yang diharapkan? Bagaimana pola-pola perubahan sosial di Indonesia? Mengapa perubahan sosial tidak selalu linear dengan imajinasi para pejuangnya?
Jika diklasifikasi terdapat dua model atau sifat perubahan sosial, yaitu evolusioner dan revolusioner. Evolusioner adalah perubahan yang terjadi secara bertahap dan lambat, karena itu memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian. Sedangkan revolusioner merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan drastis, perubahan ini berskala besar dan fundamental dalam struktur sosial atau politik.
Melihat sejarah perubahan sosial di Indonesia kedua model tersebut pernah terjadi. Model revolusioner pernah terjadi pada masa revolusi kemerdekaan dari kekuasaan kolonial ke bangsa Indonesia sendiri.
Revolusi ini relatif sukses karena berhasil mengganti sistem pemerintahan dari cengkeraman kolonial ke tangan bangsa Indonesia yang berdaulat. Sedangkan revolusi yang gagal ada dua: pertama, gerakan DI/TII yang bersobsesi mengganti sistem negara menjadi khilafah berdasar ideologi Islam; kedua, G-30 S/PKI yang gagal mendirikan sistem komunis di Indonesia.
Sedangkan perubahan evolusioner tersirat dalam berbagai gerakan maupun program baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun entitas sosial lainnnya.
Program pembangunan di era Orde Baru adalah contoh bagaimana pemerintah mencanangkan berbagai paket program dan kebijakan untuk merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk mampu tinggal landas menuju kesejahteraan dan persaingan global.
Walaupun rezim Suharto kala itu mampu menjaga stabilitas politik dan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan namun perubahan evolusioner ini membawa dua dampak negatif, yaitu: 1) kesenjangan ekonomi, baik antar daerah maupun antar kelas sosial ekonomi; 2) Ketergantungan Indonesia pada negara-negara maju.
Contoh perubahan evolusioner di Indonesia berikutnya adalah gerakan reformasi 1998. Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim otoritarianisme Suharto yang berkuasa 32 tahun membawa harapan baru adanya sintesa sistem kekuasaan yang memberi ruang kebebasan, demokratisasi, dan hak asasi manusia.
Memang dalam beberapa hal harapan itu terwujud, namun setelah 27 tahun era reformasi itu berjalan dengan pergantian 5 presiden (Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo) tak sepenuhnya semua cita-cita reformasi itu terealisasi.
Harapan bahwa ada perbaikan sistem politik menjadi lebih demokratis, partisipasi publik meningkat, dan kesejahteraan merata justru berjumpa dengan fakta oligarkhi, manipulasi kepentingan publik, dan merajalelanya korupsi.
Fakta tersebut diperunyam dengan fenomena disrupsi masyarakat rezomatik yang begitu susah diatur dan ditertibkan. Pembangunan yang mempersyaratkan adanya jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial menjadi sulit terpenuhi.
Momentum memanfaatkan bonus demografi dan peluang perubahan geopolitik global yang memberi kesempatan negara Indonesia masuk menjadi negara yang berdaya saing global seakan terbuang sia-sia. Jargon “Indonesia Emas” 2045 pun pesimis tercapai.
Peristiwa dan tragedi duka baru-baru ini menambah daftar panjang bahwa perubahan sosial tak menjamin sebuah impian yang awalnya mulia berujung pada perbaikan. Merenungi sejarah kegagalan perubahan sosial di Indonesia memunculkan pertanyaan reflektif; apa yang salah dengan gerakan sosial di Indonesia selama ini? Apa yang paling efektif membawa perubahan sosial untuk konteks bangsa yang begitu besar dan beragam ini?
Asumsi bahwa pola perubahan revolusioner tidak memungkinkan karena costnya terlalu mahal dan beresiko, maka pilihan jatuh pada pola perubahan yang bersifat evolusioner.
Namun, perubahan evolusioner ini pun butuh pra-syarat, yakni “enlighment” pola pikir. Istilah lain dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia disebut dengan “renaissance”, yaitu sebuah istilah dari bahasa Perancis yang berarti “kelahiran kembali” atau “pembaharuan”.
Renaissance merupakan gerakan budaya dan intelektual yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 hingga ke-17, yang menandai transisi dari Abad Pertengahan ke zaman modern. Salah satu hasil dari gerakan ini adalah penghargaan terhadap nilai-nilai humanisme dan cara berpikir rasional yang nantinya menjadi dasar dalam membangun sistem sosial yang lebih demokratis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Untuk konteks saat ini renaissance itu mestinya diperankan oleh entitas pendidikan. Kacaunya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia masuk dalam lingkaran setan tak berujung.
Politisasi, ideologisasi, dan pragmatisme dunia pendidikan membuatnya terjerembab dalam pusaran yang justru anti rasionalisme dan kemajuan ilmu pengetahuan. Lihatlah bagaimana stake holder pendidikan lebih sibuk urusan administratif, birokrasi, dan perjuangan ideologi primordial. Demikian halnya peserta pembelajar yang terkuras energinya oleh beban pelajaran normatif dan instrumen semu prestasi akademik.
Melihat realitas pendidikan tersebut pesimis rasanya gerakan sosial dalam berbagai bentuk, seperti gerakan demokratisasi, pemerataan ekonomi, keadilan hukum, dll. bisa terwujud.
Sebenarnya masih menyisakan satu harapan perubahan sosial yang lebih baik itu bisa disandarkan, yakni kepemimpinan. Namun sayangnya, sama dengan nasib dunia pendidikan, sistem politik saat ini juga masuk dalam lingkaran setan tak berujung dan blunder.
Memang sistem pemilu memberi ruang aspirasi rakyat disalurkan secara bebas dan terbuka siapa pemimpin yang dipilih. Namun lihatlah faktanya bagaimana perilaku pemilih di Indonesia. Pemilik suara mendasarkan pilihannya bukan karena siapa yang kompeten sebagai wakil rakyat, siapa yang amanah dan Istiqomah memperjuangkan “wong cilik”.
Namun mereka memilih karena uang, populeritas, lucu, seru, gokil, sejenis agamanya, sama sukunya, ada hubungan keluarga, dan hal-hal lain yang tak terkait dengan kompetensi sebagai wakil rakyat.
Jadi kalau hari ini rakyat disuguhi berbagai drama anggota dewan yang tak bermutu, berkhianat, public speakingnya buruk, kepekaan sosialnya tumpul, produk legislasinya mandul, pengawasannya konspiratif, dan fungsi budgetingnya ngawur, semua itu adalah cerminan bopeng wajah kita sendiri.
Demikian halnya pemimpin di ranah eksekutif, sejak dari lurah, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden tak sepenuhnya dipilih atas pertimbangan logika, rasionalitas, dan kedalaman budaya.
Inilah negeri antah-barantah yang dilingkari sengkarut tak berujung. Pola sejarah bangsa ini selalu berputar-putar, jalan di tempat, bahkan involusi. Dan begitu terus dari waktu ke waktu. Anehnya adalah bangsa ini tak pernah lelah mereproduksi harapan dan imajinasi di setiap tikungan waktu.
*) Dosen dan peneliti tinggal di Yogyakarta