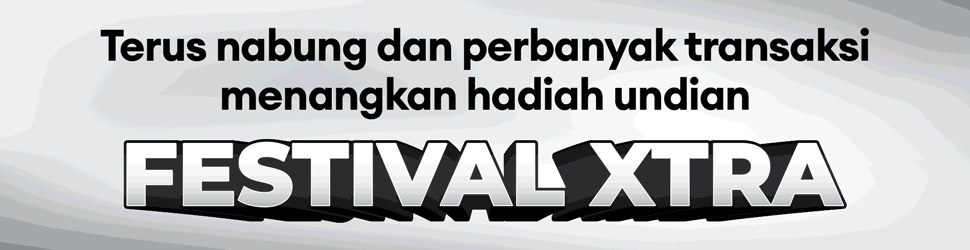Oleh Dr. Saifudin Zuhri, M.Si.*
Pada tahun 470 SM atau lebih dari 2.400 tahun yang lalu di Athena seorang filosof Yunani kuno yang bernama Socrates tidak percaya demokrasi bisa diandalkan untuk mengelola kekuasaan dengan baik. Kekuasaan yang diserahkan melalui mekanisme demokrasi dianggap sebuah spekulasi yang mempertaruhkan kekuasaan di tangan orang-orang yang tidak kompeten tetapi sah menggenggam kekuasaan. Pertaruhan ini menurut Socrates berbahaya bagi kehidupan publik itu sendiri karena demokrasi menjadi pintu masuk individu untuk memanipulasi kepentingan publik dengan dalih politik representasi.
Mengelola kekuasaan ibarat menakhodai sebuah kapal mengarungi samudera, supaya kapal mampu menerjang ombak dan menaklukkan badai dibutuhkan seorang nakhoda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang melampaui dirinya sendiri dan kompeten. Keahlian semacam itu tidaklah dimiliki semua orang yang ada dalam kapal.
Walaupun seorang nakhoda memiliki ego pribadi atau keberpihakan kepada salah satu kelompok di antar penumpang kapal, maka sang nakhoda harus mampu melampaui itu semua untuk lebih mengutamakan navigasi kapal dan keselamatan seluruh penumpang menuju satu titik tujuan bersama.
Apa jadinya ketika menentukan siapa yang pantas menjadi nakhoda ditentukan melalui voting kepada seluruh penumpang dalam kapal dengan hak suara yang sama. Sistem semacam ini akan membuka peluang bagi setiap individu untuk bersaing mendapatkan pengaruh supaya terpilih menjadi nakhoda. Celakanya adalah tidak ada jaminan bahwa kepintaran membangun pengaruh itu (elektabilitas) secara otomatis juga cakap menjalankan profesi sebagai nakhoda. Di sinilah terbuka kemungkinan individu yang sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten memegang kekuasaan mendapat legitimasi hanya gara-gara berhasil mempengaruhi opini publik sehingga mendapat suara terbanyak.
Itulah premis yang menjadi dasar argumen Socrates, yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul “Republik” (bahasa Yunani: Πολιτεία, Politeia). Dalam karya ini, Plato menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang raja-filsuf yang memiliki kebijaksanaan dan keutamaan. Plato berpendapat bahwa demokrasi tidaklah ideal karena dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan. Plato tidak mempercayai demokrasi sebagai cara yang dapat diandalkan menemukan pemimpin yang ideal. Sebagai antitesisnya Socrates maupun Plato mempercayakan kepemimpinan pada diri seorang filosof.
Pada era Yunani kuno dimana filosof yang menjadi sumber pencerahan dari cara pandang mitologi dan irasional dipercaya merepresentasikan kepemimpinan ideal. Para filosof dianggap sebagai sosok yang mencerminkan keutamaan dan kebijaksanaan yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Itulah mengapa Socrates dan juga Plato memberi keistimewaan kepada para filosof dalam sistem sosial.
Simpulan Socrates dan Plato yang tidak percaya dengan sistem demokrasi dengan menawarkan kepemimpinan ideal kepada para filosof memang berpotensi menciptakan sistem kekuasaan monarkhis atau paling tidak oligarkhis, yaitu pembatasan otoritas kekuasaan hanya di tangan satu orang atau sekelompok kecil, yakni para filosof.
Namun jika ditelaah premis yang dibangun menarik untuk dijadikan alat analisis terhadap fenomena praktik demokrasi hari ini di Indonesia. Bukan dalam rangka menolak demokrasi yang sudah disepakati oleh bangsa ini sebagai sistem tatakelola kekuasaan namun untuk mengkritisi bagaimana praktik demokrasi hari ini.
Hari-hari ini muncul fenomena perselisihan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri tentang retret bagi kepala daerah yang baru saja dilantik. Probowo sebagai presiden dan kepala pemerintahan memprogramkan kepala-kepala daerah yang baru saja dilantiknya untuk mengikuti retret tgl 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang.
Program ini bertujuan untuk koordinasi dan membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Program retret ini menjadi heboh ketika Megawati, ketua umum (Ketum) PDIP, menerbitkan surat perintah untuk kepala daerah yang berasal dari kader partainya untuk tidak menghadiri acara tersebut. Tentu saja aksi boikot Ketum partai berlambang moncong putih itu mengundang polemik dan berbagai spekulasi tentang hubungan antara Prabowo dan Megawati.
Konon aksi boikot tersebut merupakan titik kulminasi kekecewaan Megawati kepada Prabowo yang tidak menunjukkan rasa empati kepada Megawati dan juga PDIP yang merasa tersakiti karena merasa dikhianati oleh Jokowi. Megawati dan kader PDIP berharap Prabowo setelah terpilih sebagai presiden, walaupun didampingi oleh Gibran sang putra mantan Presiden Jokowi, menyetujui narasi yang dibangun bahwa Jokowi harus dijauhi, dibenci, dihinakan,dan bahkan diadili.
Namun dalam berbagai kesempatan Prabowo tak bergeming, sebaliknya dalam sebuah kesempatan di peringatan hari ulang tahun partai Gerindra justru menunjukkan rasa respek, apresiasi, dan bahkan memberi panggung kehormatan bagi Jokowi untuk memberi sambutan. Puncaknya adalah ditahannya sang Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK karena terjerat kasus korupsi dan tindakan kriminal menghalang-halangi penegakan hukum.
Sikap Prabowo yang tidak sesuai dengan harapan narasi yang dibangun oleh Megawati dan para kadernya tentu saja sangat mengecewakan dan menyakitkan. Aksi boikot Megawati terhadap program retret kepala daerah adalah ekspresi dari puncak kekecewaan bahkan kemarahan terhadap sang presiden yang tidak mengamini narasi yang dibangun. Bahkan konon patut diduga aksi massa mahasiswa di berbagai daerah yang mengusung tema demontrasi dengan judul “Indonesia Gelap” bisa diletakkan dalam konteks konstelasi politik tersebut.
Terlepas materi yang dinarasikan oleh PDIP sebagai partai oposan dan gerakan demokrasi yang mengkritisi pemerintah, bentuk respon dan cara-cara yang ditempuh oleh Megawati dengan memboikot program retret bagi kepala daerah menyiratkan makna politik sebagai berikut:
1) Membenarkan kekhawatiran Socrates terpapar di atas bahwa demokrasi acapkali menjadi pintu masuk individu yang tidak kompeten memiliki legitimasi untuk berkuasa. Mekanisme demokrasi yang sudah dilalui walau hanya dipenuhi prosedurnya saja sudah mencukupi untuk melegitimasi sebuah kekuasaan jika memenangi sebuah kontestasi, bahkan walau dengan menghalalkan segala cara sekalipun. Legitimasi prosedural inilah yang mendekonstruksi nilai moral yang mestinya bersifat “das sollen” dan koersif menjadi lebih pragmatis dan mengalami instrumentalisasi di bawah kepentingan politik. Tidak ada jaminan bahwa elit-elit politik yang sekarang memegang kekuasaan, baik di partai politik maupun pemerintahan, pasti memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan mampu memproduksi kebijakan publik yang tepat, namun karena secara sah memegang kekuasaan maka di tangan merekalah nasib dan arah sebuah bangsa akan ditentukan. Itulah mengapa retret kepala daerah memunculkan respon publik dan polemik yang cenderung kekanak-kanakan dari elit-elit politik.
2) Idealnya ketika seseorang menduduki jabatan sebuah lembaga, baik partai politik maupun pemerintahan, segala keputusan yang diambil bahkan hingga perilakunya mestinya merepresentasikan institusinya, bukan ego dan kepentingan pribadinya. Dalam merespon program retret Megawati lebih mengekspresikan dimensi afeksi dirinya secara emosional daripada tindakan konstitusional dalam kapasitasnya sebagai Ketum partai dan mantan presiden. Akibatnya, narasi yang berkembang lebih sebagai ungkapan dimensi afektual (perasaan), seperti rasa benci, prejudice, dan membangun narasi yang cenderung mendelegitimasi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi memang menjadi oposisi, kritik, dan kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, namun pembelaan marwah partai secara sepihak, apalagi sudah ditemukan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum partai, adalah sikap yang berlebihan dan tidak proporsional. Sebagai mantan presiden mestinya Megawati cukup berpengalaman untuk membangun kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
3) Kasus polemik retret kepala daerah menggambarkan kegagalan komunikasi politik antar elit atau antar lembaga politik. Di tengah massifnya penggunaan media sosial dalam komunikasi politik, rendahnya kemampuan komunikasi politik antar elit memperkeruh atmosfir komunikasi menjadi semakin tidak terpola dan tidak terstruktur. Dalam arus komunikasi yang liar itulah upaya merajut kohesi sosial (kesatuan dan persatuan) menjadi kian sulit dilakukan karena acapkali publik mudah terpolarisasi dalam narasi saling membenci dan saling menafikan. Dalam banalitas komunikasi inilah semakin sulit memilah mana informasi yang valid dan fiktif, fakta dan fitnah, mana yang berguna dan sia-sia. Semua tenggelam dalam kebisingan perdebatan dan perseteruan yang hampa.
4) Pembangkangan beberapa kepala daerah untuk hadir dalam acara retret semakin memperkuat signal bahwa otonomi daerah yang lama diundangkan dengan harapan mengakhiri sentralisme yang dulu pernah terjadi di era Orde Baru, ternyata masih lemah realisasinya untuk mengatur pola hubungan pusat dan daerah. Banyak kepala daerah (terutama yang berasal dari partai oposan seperti PDIP) mengalami loyalitas ganda antara tunduk pada Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dengan ketua partai politik karena masih juga menyandang predikat “petugas partai”. Jika fenomena ini tak kunjung diselesaikan maka akan menghambat sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah.
5) Kalaupun program retret yang dicanangkan Presiden Prabowo itu dikritik maka yang perlu dipersoalkan lebih pada sisi bentuk, makna, dan efektifitas untuk kepemimpinan sipil, bukan pada aksi boikot. Pada satu sisi retret memang bertujuan mulia, yakni untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah, namun di sisi lain bagaimanapun pemilihan bentuk kegiatan semacam itu bias militerisme. Prabowo yang berlatar belakang militer perlu diimbangi dengan pendekatan kepemimpinan sipil. Kurikulum retret perlu dirumuskan lebih komprehensif dan holistik sehingga mengakomodasi berbagai aspek untuk membekali kepala daerah yang akan menjadi pelayan publik di daerahnya masing-masing, baik dari sisi narasumber, motodologi penyampaian, hingga materi yang disampaikan.
Itulah perenungan terhadap polemik retret untuk kepala daerah. Memang demokrasi sudah dipilih oleh bangsa ini dalam mengelola kekuasaan dan menentukan kepemimpinan karena itu tidak mungkin menganulir demokrasi sebagaimana yang digagas Socrates dan Plato, namun untuk memaknai demokrasi itu sendiri perlu dikawal oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati sehingga tidak dibajak dan dimanipulasi oleh elitnya sendiri. Jika tidak maka kekhawatiran Socrates dan Plato bahwa demokrasi justru memunculkan kekacauan dan ketidakstabilan akan terbukti.
*) Dosen STIE SBI, peneliti PR2MEDIA, dan penggiat Perhimpunan Warga Pancasila (PWP), tinggal di Yogyakarta