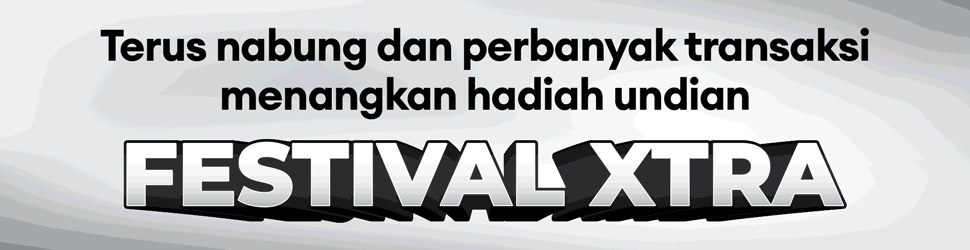*Oleh Dr. Saifudin Zuhri, M.Si.
“Tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan abadi, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri”. Itulah adagium yang begitu populer yang seakan menjadi postulat di dunia politik. Pernyataan tersebut kembali ditegaskan oleh polah tingkah elit politik di negeri ini. Seorang politisi atau partai politik yang awalnya berseteru sedemikian keras dan brutal di lain waktu tiba-tiba berangkulan dengan mesra seakan tak terjadi apa-apa. Demikian halnya sebaliknya, para elit atau beberapa parpol yang berkongsi dalam satu koalisi dalam dinamika selanjutnya pecah kongsi bahkan saling membenci dan mengunci.
Fenomena terbaru adalah pertemuan dua tokoh politik yang sebelumnya saling berseteru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 hingga membelah warga ibukota itu dalam konflik politik identitas yang begitu tajam. Residu dari konflik politik identitas itu bahkan bereskalasi dalam Pilpres 2019 yang lagi-lagi membelah bangsa ini dalam kategori “cebong” dan “kampret”, sebuah istilah yang menggambarkan betapa tidak beradabnya nuansa konflik itu hingga menjuluki kubu lawan saja dengan istilah nama binatang.
Sikap politik yang berbalik arah semacam itu bukanlah fenomena baru dalam lanskap politik Indonesia, sebelum kasus Ahok vs Anies dan cebong vs kampret juga pernah terjadi di kasus pemilihan presiden pasca runtuhnya orde baru. Megawati yang dijagokan PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999 justru kalah oleh poros tengah yang digalang oleh Amien Rais yang mengusung Abdurrahman Wahid (Gusdur). Namun belum berselang lama oleh Amien Rais pula Gusdur diturunkan melalui impeachment di MPR yang diketuai oleh Amien Rais pula. Selain contoh kasus tersebut di atas masih terdapat berbagai fenomena individual elit-elit politik yang menggambarkan betapa pragmatisnya perilaku politik elit negeri ini.
Istilah pragmatisme itu sendiri merupakan salah satu aliran filsafat yang muncul pada abad ke-19. Pragmatisme mengajarkan bahwa segala sesuatu dianggap benar jika memiliki asas kemanfaatan atau nilai guna. Dalam sejarah filsafat pragmatisme lahir dari konteks dunia Barat dan berkembang khususnya di benua Amerika. Pencetus pemikiran pragmatisme adalah seorang filsuf Amerika, Chales Sanders Peirce (1839–1914) yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842–1910) dan John Dewey (1859–1952).
Jika latar belakang kelahiran pragmatisme sebagai upaya untuk menjawab persoalan kehidupan manusia supaya lebih berorientasi pada asas manfaat, maka ketika dikontekstualisasi pada ranah politik kontemporer tidaklah selalu berkonotasi positif. Pragmatisme dalam dunia politik praktis lebih diartikan sebagai penyederhanaan tujuan politik hanya sekedar memperoleh kepentingan kekuatasaan yang bersifat material, finansial, dan pelanggengan kekuasaan. Apa yang dianggap berharga dalam pragmatisme politik adalah terjaminnya kepentingan pribadi atau golongan, kalaupun ada manfaat maka yang dimaksud adalah manfaat instrumental bendawi untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya. Sementara nilai-nilai yang berdimensi moralitas, etis, dan kepentingan publik justru tersubordinasi.
Setidaknya terdapat empat faktor mengapa fenomena pragmatisme politik Indonesia menguat akhir-akhir ini, yaitu sebagai berikut :
1) Matinya ideologi partai politik. Ideologi sebagai nilai prinsip yang menjadi fundamen partai memudar seiring pergeseran orientasi parpol dari memperjuangkan nilai idealisme yang menjadi ruh ke kepentingan instrumental pragmatis, seperti materi, kekuasaan, dinasti, dll. De-ideologi parpol ini bukan hanya semakin menjauhkan parpol dari visi misi mulanya namun mereduksi parpol yang semestinya merepresentasikan kepentingan konstituennya lebih sebagai alat elit parpol untuk melanggengkan kekuasaan pribadi dan mengakses sumberdaya kekuasaan yang bersifat pragmatis.
2) Politik transaksional. Tak dipungkiri liberalisasi demokrasi mendorong segala aspek yang terlibat dalam mekanisme kekuasaan melakukan pertukaran yang lebih mirip mekanisme ekonomi pasar. Kekuasaan menjadi komoditas yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan menjual suaranya ke elit politik sebagai pembeli untuk kemudian dijual kembali ke level pasar yang lebih tinggi untuk melipatgandakan keuntungan. Dalam proses transaksional ini maka uang menjadi faktor penting karena uang bukan hanya alat tukar paling praktis dan cepat namun uang mampu merepresentasikan komoditas apapun dalam simbul-simbul angka finansial. Dari sinilah money politic tak terelakkan.
3) Sistem multipartai. Jumlah partai yang begitu banyak dan beragam berakibat pada sulitnya meraih kemenangan mutlak bagi kontestan Pemilu di Indonesia. Karena itu bagi kekuatan politik yang potensial menang sekalipun (apalagi yang kalah) dituntut memiliki keterbukaan untuk menggalang koalisi dengan parpol lain untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik supaya lebih solid, sejak dari tahap pencalonan, kampanye, kemenangan hingga ketika menduduki kekuasaan pemerintah sekalipun untuk menjaga stabilitas politik. Dalam mengatasi kompleksitas dan atmosfir politik yang begitu dinamis itulah pragmatisme menjadi hal paling mudah pengukurannya.
4) Pengukuran kinerja politik bersifat langsung dan jangka pendek. Dalam sistem budaya politik di Indonesia nampaknya belum terbiasa membangun sistem yang bersifat impersonal dan rasional. Sebaliknya, konstituen akan mengukur terhadap kinerja dan reputasi pemimpin atau para wakil rakyat dengan indikator yang bersifat langsung, fisik, dan berjangka waktu pendek. Sebagai contoh seorang pemimpin (Presiden sampai kepala desa dan seorang legislatif) dianggap sukses dan baik jika hadir dan memberi bantuan secara langsung kepada orang per orang. Publik tidak memiliki kemampuan analisis terhadap kebijakan yang bersifat sistemik yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk publik. Budaya pengukuran kinerja politik secara langsung dan jangka pendek ini oleh politisi tidak diupayakan dengan pendidikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi namun justru dimanfaatkan para elit politik untuk memudahkan berbagai intrik politik yang pragmatis.
Fenomena pragmatisme politik di Indonesia akhir-akhir ini seakan mengafirmasi teori politik kekuasaan yang dikemukakan oleh Machiavelli bahwa untuk mencapai tujuan dianjurkan menghalalkan segala cara, lain dari itu realitas politik dimaksud juga menjadi lonceng kematian politik aliran di Indonesia setelah mati suri di era rezim otoriter Suharto dan sempat bangkit di Pemilu pertama 1999 era reformasi.
Pragmatisme elit politik akan semakin menjadi-jadi di negeri ini terlihat dari indikasi munculnya berbagai fenomena konsolidasi antar elit politik akhir-akhir ini untuk menyongsong Pemilu 2029 padahal pesta demokrasi baru saja usai. Terlebih dengan keputusan MK terbaru yang menghapus Presidential Threshold sehingga membuka peluang semua Parpol untuk mengusung calonnya sendiri-sendiri. Dengan demikian konstelasi politik akan semakin dinamis, kompleks, dan penuh kejutan.
Di tengah prediksi tersebut maka demokrasi harus tetap dikawal untuk mengeliminasi berbagai upaya pembajakan demokrasi oleh elit politik itu sendiri. Diperlukan penguatan kesadaran demokrasi di kalangan warga negara supaya tidak gampang termanipulasi intrik politik para elit yang tanda-tandanya akan semakin pragmatis.
*(Penulis adalah dosen dan peneliti PR2MEDIA Yogyakarta)