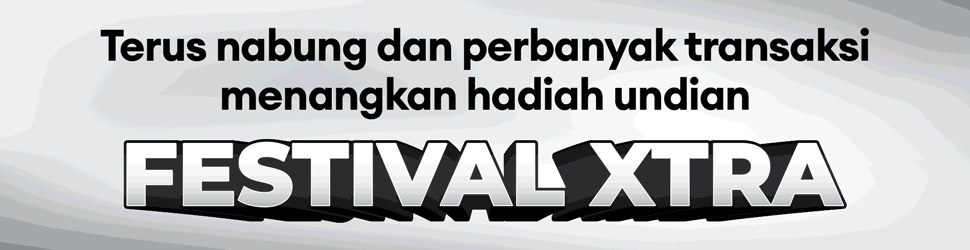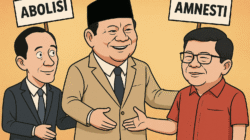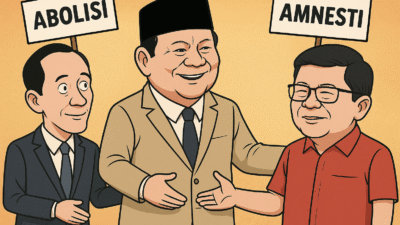Oleh : Herman Dirgantara*
Menyampaikan kritik yang sah merupakan fondasi demokrasi. Namun, di era digital, batas antara kritik dan pencemaran nama baik acapkali kabur.
Belakangan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada perkara pengujian undang-undang yang menyoroti Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) serta Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MK melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 tertanggal 29 April 2025, menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya merujuk pada individu atau perseorangan, alih-alih menunjuk institusi Pemerintah dan sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu seperti institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
Artinya, hanya orang pribadi atau individu yang dapat mengajukan pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik secara digital.
Langkah ini menjadi penyeimbang antara perlindungan nama baik dengan kebebasan berpendapat di ruang digital yang semakin kompleks dan luas.
Implikasi hukum dari putusan ini tidak dapat disepelekan. Dalam episentrum teori perlindungan hukum, kejelasan norma pidana adalah prasyarat mutlak untuk melindungi hak-hak asasi warga (Hadjon, 1987).
Tidak heran bila Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang atas perlindungan hukum yang adil dan berkepastian hukum. Putusan MK ini tak ayal menunjukkan keberpihakan pada prinsip tersebut dengan menolak ‘penafsiran karet’ yang selama ini menjadi celah kriminalisasi.
Selain mempertegas subjek hukum yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik, MK juga menafsirkan ulang frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang dianggap terlalu kabur.
MK menegaskan bahwa frasa “suatu hal” dalam norma tersebut harus dimaknai secara terbatas, yaitu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.
Berdasarkan teori penafsiran konstitusi, penekanannya ialah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat dan proporsional.
Sebagaimana dijelaskan oleh Saldi Isra (2019), dalam sistem hukum yang demokratis, penafsiran konstitusi berfungsi bukan sekadar menjabarkan norma, melainkan menjaga agar hak-hak fundamental tidak dikebiri atas nama kepentingan umum yang kabur.
Putusan MK merefleksikan fungsi itu dengan mencegah perluasan makna hukum pidana secara berlebihan.
Putusan MK turut mempertegas pentingnya keberadaan unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang kerap digunakan untuk mempidanakan seseorang yang diklaim menyebarkan kebencian.
Dalam konteks ini, MK menekankan bahwa profesi seperti wartawan, akademisi, atau advokat harus tetap mendapat ruang untuk menjalankan fungsinya selama tidak melampaui batas konstitusional.
Dalam episentrum teori hak asasi manusia, kebebasan berekspresi yang sah merupakan hak fundamental. Tentu dengan catatan, bukan hak yang absolut. Hanya ekspresi yang mengarah pada kekerasan atau diskriminasi yang boleh dibatasi.
Hal demikian seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Pada titik ini, peran MK sangat penting sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak asasi warga. Putusan ini memberi kerangka hukum yang lebih proporsional dan terukur dalam membedakan mana kritik yang sah dan mana yang sebetulnya ujaran kebencian.
Misalnya, seorang jurnalis yang menyebarkan informasi untuk kepentingan publik tidak dapat dipidana selama tidak melanggar ketentuan “tanpa hak”. Ini sejalan dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi dan martabat setiap orang.
Putusan MK ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dengan kebebasan berpendapat di era digital yang kian kompleks.
Dengan memperjelas batasan hukum, putusan ini mencegah UU ITE disalahgunakan sebagai perkakas membungkam kritik dan aspirasi masyarakat.
Teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick (2001) juga relevan di sini, yakni hukum yang baik harus mampu merespons tuntutan keadilan dalam masyarakat, alih-alih terhebat sebagai alat kekuasaan.
Tafsir konstitusi MK mencerminkan paradigma hukum responsif sebab melindungi hak asasi manusia, namun di saat bersamaan juga memastikan hukum tidak disalahgunakan oleh institusi yang anti-kritik
Putusan ini memberi harapan bahwa hukum dapat kembali menjadi pelindung, bukan penindas. Namun ke depan, tantangannya adalah memastikan agar tafsir MK ini benar-benar diinternalisasi oleh aparat penegak hukum dalam praktik.
Di era digital, ruang publik virtual adalah arena baru demokrasi. Jika hukum gagal beradaptasi dan justru menjadi instrumen pembungkaman, maka yang terancam bukan hanya kebebasan mengkritisi, melainkan demokrasi itu sendiri.
Beruntung, kehadiran putusan ini seolah membungkam balik upaya pembungkaman suara-suara kritis publik di era digital melalui kriminalisasi. Putusan MK ini tentu bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju regulasi digital yang adil, partisipatif, dan konstitusional.
*penulis adalah Analis Hukum dan Politik dari Gajah Mada Analitika
Artikel ini telah tayang di Kompas.com pada tanggal 3 Mei 2025 dengan judul : Membungkam Pembungkaman Demokrasi Digital oleh penulis yang sama.