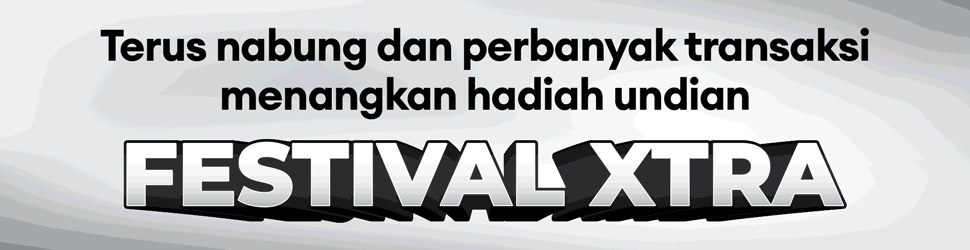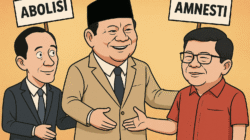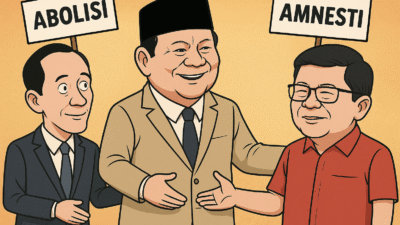- Oleh Dr. Saifudin Zuhri, M.Si
Cerita lama itu selalu berulang, kisah nestapa petani yang terombang-ambing di tengah hukum pasar.
Teori Adam Smith tentang hukum pasar yang menghibur bahwa dalam mekanisme pasar ada “the invisible hand” yang akan mendorong titik keseimbangan (equilibrium) ternyata tidak terbukti. Pasar tetap dikuasai oleh pemain yang memiliki sumber daya dominan hingga memonopoli pasar yang katanya sempurna itu, sementara petani meratapi nasibnya di pojok pasar dalam kekalahannya.
Berita tentang carut-marut harga komoditas pertanian selalu berulang dari tahun ke tahun. Beberapa komoditas pertanian seperti cabe, sayur-sayuran, buah lokal, dll akhir-akhir ini naik drastis di kala produksi menurun. Petani yang mestinya menikmati kenaikan harga harus gigit jari karena tak memiliki stok untuk dijual. Sebaliknya ketika panen melimpah harga jatuh yang kadang tidak mencukupi untuk biaya produksi.
Memang itulah hukum pasar dimana harga ditentukan oleh korelasi antara supply and demand. Persoalannya adalah mampukah petani negara agraris ini menghadapi hukum pasar itu? Apa problem mendasar yang dihadapi petani selama ini? Sejauhmana program pertanian yang dijanjikan pemerintah sekarang ini mampu memberdayakan dan mensejahterakan petani?
Untuk mengikuti mekanisme hukum pasar dituntut memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika pasar itu sendiri. Sedangkan petani di negeri ini memiliki berbagai problem fundamental yang dari dulu hingga kini tidak tersentuh. Tragisnya, di satu sisi petani justru menjadi korban politik dari tangan-tangan kekuasaan.
Dulu di era orde lama masyarakat petani menjadi korban agitasi partai komunis yang menjanjikan land reform dan impian masyarakat tanpa kelas, berdirinya organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia) adalah contoh yang pada akhirnya menjebak kaum petani dalam gerakan G/30S-PKI . Di era orde baru petani menjadi korban mobilisasi politik untuk mendukung status quo penguasa, walaupun dibentuk Kelompencapir yang seakan-akan mewadahi petani namun hakikatnya sebagai alat mobilisasi untuk mendukung partai Golkar kala itu.
Di era reformasi teramat banyak janji di tengah praktik politik transaksional. Sejumlah janji program dan paket bantuan akan diberikan kepada petani, seperti cetak lahan sejuta hektar, subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi, dana stimulus untuk petani milennial, hingga program ketahanan pangan nyaring diperdengarkan. Namun sebegitu jauh dalam realitasnya tetap saja nasib petani tak beranjak.
Jika direnungkan lebih dalam ditemukan sejumlah persoalan mendasar mengapa realitas petani di Indonesia tak beranjak nasibnya, berikut di antaranya;
1) Pekerjaan petani bukanlah pilihan, namun sebuah kepasrahan dan keterpaksaan. Dalam hirarki jenis pekerjaan di Indonesia petani menduduki kasta terbawah yang dipilih pencari kerja di Indonesia. Berikut urutan kasta jenis pekerjaan di Indonesia: Pegawai Negeri (ASN, TNI, POLRI), profesional di perusahaan bonafide, pengusaha, pedagang, buruh pabrik, dan petani. Ketika pencari kerja melamar di jenis pekerjaan kasta atas tidak diterima maka pertanian menampung pilihan paling rendah, dan itupun masih dibagi dalam dua kelompok, yaitu petani pemilik lahan dan buruh tani. Dengan demikian menjadi petani adalah keterpaksaan dan kepasrahan. Dengan realitas semacam ini sulit mengupgrade nasib petani, bahkan dari sisi etos atau motivasi sekalipun.
2) Dalam persepsi petani menanam bukanlah sebuah ilmu pengetahuan, namun lebih sebagai tradisi dan kebiasaan. Perbedaannya, jika pertanian diobyektivikasi sebagai bagian dari ranah ilmu pengetahuan maka terbuka untuk dikembangkan berdasar hasil penelitian ilmiah sehingga akan menjadi lebih inovatif. Namun ketika menanam menjadi bagian dari tradisi maka akan cenderung stagnan karena bertani adalah pengulangan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun. Konsep kosmologis pertanian tradisional semacam itu memang satu sisi mengandung nilai local wisdom namun di sisi lain sulit untuk adaktif dengan tuntutan perubahan zaman.
3) Program pembangunan pertanian bukan hanya persoalan infrastruktur, investasi, penanaman, namun juga dituntut sustainabilitas pemeliharaan tanaman itu sendiri. Terdapat banyak kasus ketika pemerintah mendorong petani untuk menanam berbagai varietas tanaman namun tidak dibarengi dengan sistem perawatannya, akibatnya petani tidak siap menghadapi berbagai ancaman gagal panen, seperti serangan hama dan cuaca. Serangan hama dan cuaca masih menjadi momok bagi petani yang belum terjawab hingga hari ini. Sentuhan teknologi belum signifikan dan belum maksimal dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4) Lemahnya kinerja stakehorder’s pengembang pertanian. Terdapat dua lembaga penting yang mestinya bertanggung jawab di sektor pertanian, yakni Dinas Pertanian dan lembaga pendidikan khususnya yang membuka program studi pertanian. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana mental birokrasi lembaga pemerintah yang mestinya bertanggung jawab terhadap obyeknya justru tereduksi oleh beban politik birokrasinya sendiri. Demikian halnya lembaga pendidikan yang mestinya menjadi ujung tombak pengembangan ilmu pertanian dan temuan teknologi terbarukan juga terbebani oleh imperasi rezim adminitratif. Lihatlah bagaimana laboratorium dan peralatan praktek di berbagai lembaga pendidikan pertanian mangkrak dan hanya diadakan untuk mengakses dana hibah dari pemerintah maupun lembaga founding. Yang juga memprihatinkan bagaimana mental dan kharakter alumni lembaga pendidikan yang tidak enjoy di sektor pertanian dan justru memburu pekerjaan di perkantoran atau perkotaan.
5) Untuk pemberdayaan petani tidak cukup hanya didorong di sektor produksi namun sektor distribusi juga harus ditangani. Di sektor distribusi terdapat dua titik lemah, yaitu pertama, dukungan regulasi yang belum memadai sehingga tidak ada intervensi pasar oleh pemerintah. Komoditas pertanian dibiarkan bersaing secara terbuka dengan produk pertanian dari negara lain tanpa proteksi dan kehadiran negara di tengah rendahnya kualitas produk pertanian kita. Kedua, ekosistem tataniaga hasil pertanian tidak melibatkan petani itu sendiri, namun dikuasasi oleh pihak lain yang mengambil oportunity lebih besar, seperti tengkulak, rentenir, makelar, dan mafia produk pertanian. Sementara lembaga-lembaga yang bertugas menjaga keseimbangan nilai kelangkaan, seperti Bulog, KUD, dan lain-lain kurang kapabel mengikuti kecepatan dinamika pasar.
Itulah berbagai permasalahan klasik, mendasar, dan seakan permanen di sektor pertanian di negara agraris beriklim tropis ini. Obsesi pemerintah mendorong kemandirian pangan dengan mencanangkan berbagai program bantuan tidak menjadi jaminan merubah nasib petani jika problem-problem tersebut tak tersentuh. Jangan terlalu kaget jika rasa sambal kita tak sepedas nasib petani yang kian hari kian sepi dan sendiri. Di tengah kesendirian dan kesepian para petani itu lari ke dunia mistik untuk mengadukan nasibnya. Dan begitulah kisah hidup kaum petani di negeri ini yang berulang dari masa ke masa.
*Penulis adalah Peneliti dan Pendidik di Yogyakarta